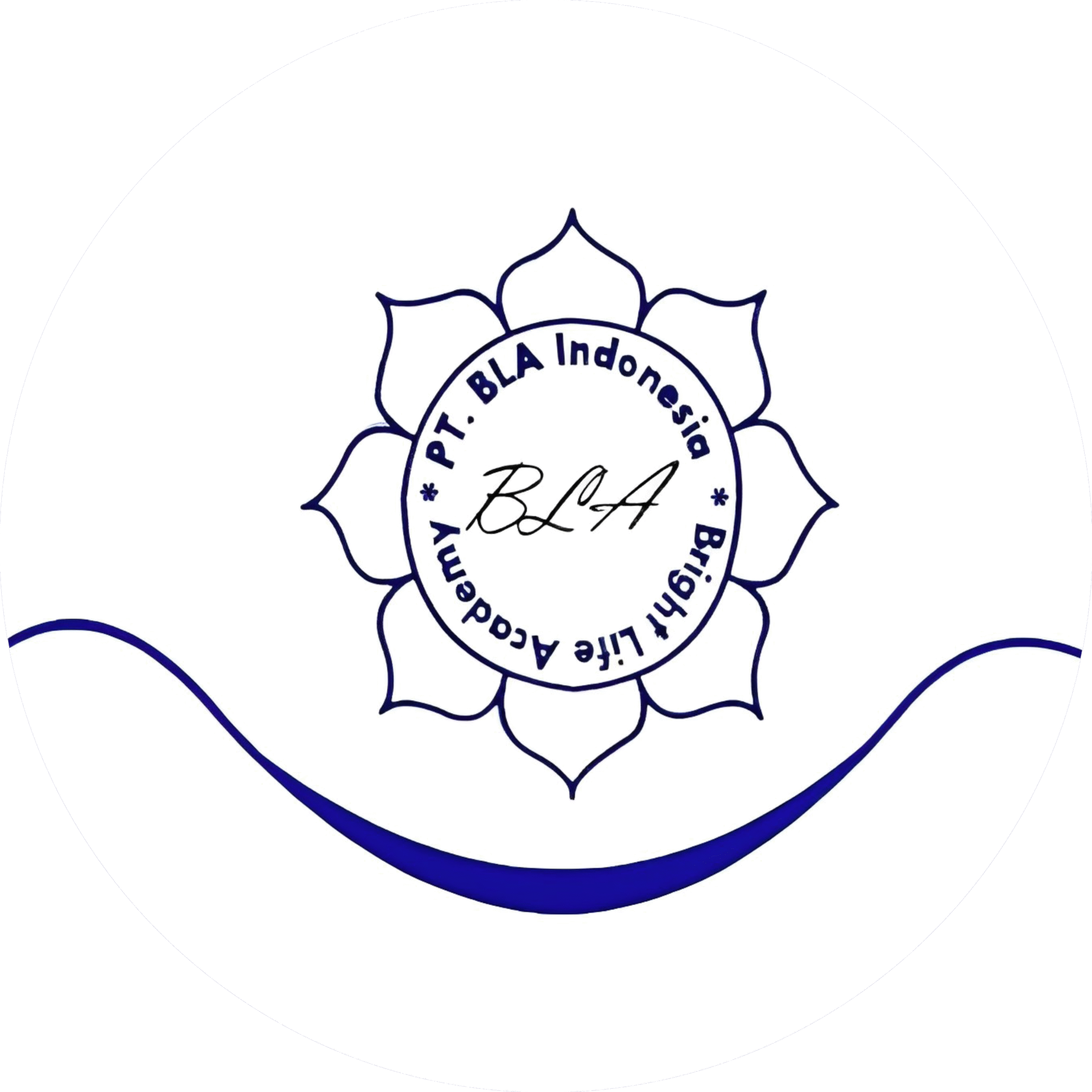Strategi hebat bukan jaminan sukses.
“Mengapa banyak organisasi pintar tetap gagal?”
“Apakah benar strategi hebat menjamin sukses?”
“Kalau strategi sudah ada, lalu apa yang salah?”
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Di era di mana framework, best practice, dan blueprint transformasi tersedia melimpah, kegagalan eksekusi tetap jadi kenyataan pahit: penelitian McKinsey menunjukkan bahwa sekitar 70% inisiatif transformasi gagal mencapai targetnya — bukan karena tidak ada rencana, melainkan karena rencana itu tidak ‘dimiliki’ oleh orang-orang yang harus menjalankannya. McKinsey & Company
Strategi tanpa pemilik: analogi sederhana
Bayangkan organisasi memiliki peta jalan (strategy map), kompas (OKR), dan kendaraan (teknologi). Namun tidak ada yang memutuskan untuk melangkah. Tanpa seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar memiliki outcome, peta jalan tetap menjadi dokumen—cantik, terstruktur, tetapi tidak bergerak. Itu terjadi berulang kali, baik di perusahaan besar yang menganggarkan jutaan dollar untuk konsultasi, maupun program publik yang terlihat sempurna di dokumen kebijakan namun mandek di lapangan.
Dua ilustrasi langsung
- Corporate example. Sebuah perusahaan multinasional mengadopsi roadmap digitalisasi kelas dunia. Namun staf garis depan memandangnya sebagai “proyek manajemen”—sesuatu yang bukan milik mereka—maka penggunaan alat dan proses baru tidak konsisten; inisiatif tidak menyentuh kinerja operasional.
- Public sector / NGO. Rencana transformasi pendidikan nasional bisa lengkap di dokumen, tetapi guru dan birokrat di daerah tidak merasakan kepemilikan atas tujuan itu—hasil: implementasi berhenti atau terdistorsi.
Mengapa ini terjadi? Empat hambatan budaya yang mematikan eksekusi
Organisasi gagal “menghidupkan” strategi karena pola kultur yang sistemik. Berikut hambatan utama yang sering saya jumpai (dan riset juga mengonfirmasi efeknya):
- Budaya blame-game
Ketika kegagalan terjadi, energi organisasi terkuras untuk mencari kambing hitam—bukan menganalisis akar masalah dan memperbaiki. Harvard Business Review menyebut budaya menyalahkan (blame culture) sebagai racun yang menghambat pembelajaran dan kolaborasi; organisasinya menjadi defensif, bukan adaptif. Harvard Business Review - Silos fungsi-fungsi
Unit bekerja seperti pulau—marketing, operasional, keuangan, HR punya target sendiri tanpa rasa memiliki pada outcome bersama. Patrick Lencioni (The Five Dysfunctions) bahkan menyebut kebuntuan antar-tim sebagai sumber keruntuhan eksekusi. Akhirnya, strategi lintas-fungsi yang kompleks tidak pernah terintegrasi. - Mindset compliance, bukan commitment
Banyak karyawan menjalankan tugas sesuai SOP (compliance), tetapi tidak mengambil tanggung jawab atas hasil (commitment). Gallup melaporkan bahwa tingkat keterlibatan (engagement) karyawan global rendah—hanya sekitar 21% engaged—yang berarti mayoritas tidak punya keterikatan emosional terhadap tujuan organisasi. Tanpa engagement, ownership sulit tumbuh. Gallup.com - Kepemimpinan yang tidak menumbuhkan kepemilikan
Transformasi menuntut perilaku baru di level perilaku sehari-hari—itu artinya pemimpin harus menciptakan kepemilikan luas. McKinsey menemukan bahwa di banyak transformasi yang gagal, organisasi tidak berhasil membangun ownership di garis depan; hanya 39% responden melaporkan adanya kepemilikan yang memadai dalam perubahan. Tanpa ownership di garis depan, strategi tetap teori. McKinsey & Company
Apa kata teori dan praktisi tentang ownership?
Jocko Willink & Leif Babin menyederhanakan inti ini: “Leaders must own everything in their world. There is no one else to blame.” — prinsip yang menempatkan tanggung jawab penuh pada pemimpin sebagai katalis budaya ownership. Goodreads
Dari perspektif perubahan organisasi (change management), tokoh seperti John Kotter menekankan perlunya “coalition” dan “engagement” agar perubahan berskala berhasil—yang sejatinya adalah unsur kepemilikan yang disebarluaskan, bukan dikelola sentralistik. Tanpa ownership, “sponsor” formal saja tidak cukup; perilaku baru tidak menempel.
Dampak praktis: apa yang hilang ketika ownership tidak ada
- Energi organisasi terbuang pada pembelaan diri dan politik internal, bukan pada solusi.
- Keputusan melambat karena setiap hal harus direfer ke atas (micromanagement) —atau sebaliknya, tim bawah menunggu instruksi (paralysis by analysis).
- Inovasi tersendat karena orang takut bertanggung jawab atas risiko kecil; budaya belajar dari kegagalan tidak ada.
- ROI inisiatif turun—investasi strategi tinggi, namun manfaat nyata rendah karena gap antara rencana dan pelaksanaan.
Budaya Organisasi yang Menghambat Ownership — versi lebih rinci, evidence-based, dan praktis
Banyak organisasi punya strategi matang — roadmap, KPI, teknologi — tapi gagal mengeksekusi. Penyebabnya sering bukan strategi itu sendiri, melainkan budaya organisasi yang mematikan rasa kepemilikan (ownership). Di bawah ini saya kembangkan empat hambatan budaya utama secara mendalam: apa itu, tanda-tandanya, bukti/teori pendukung, dampak praktis, dan langkah intervensi cepat + metrik yang bisa dipakai untuk mulai memperbaiki.
1) Budaya Blame Game — definisi, tanda, dampak, dan apa yang dilakukan
Apa itu?
Budaya di mana individu/kelompok lebih cepat mencari siapa yang disalahkan ketimbang mencari akar masalah dan solusi. Reaksi pertama terhadap kegagalan adalah defensif dan mencari kambing hitam.
Tanda-tanda yang bisa diamati
- Rapat post-mortem berubah jadi sesi menyalahkan individu, bukan pembelajaran.
- Orang menyembunyikan informasi/masalah karena takut konsekuensi.
- Bahasa yang muncul: “bukan salah saya”, “itu di luar kendali kami”, atau “itu bukan tugas saya”.
Data & teori yang mendukung
HBR dan literatur manajemen menyebutkan bahwa budaya menyalahkan menghambat pembelajaran organisasi dan kolaborasi — dan perusahaan yang ingin berubah harus menyingkirkan mekanisme blame agar orang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki. Harvard Business Review+1
Dampak praktis
- Energi dihabiskan untuk membela diri → produktivitas dan inovasi turun.
- Kesalahan disembunyikan → masalah berulang dan risiko besar terakumulasi.
- Psychological safety hilang → orang enggan bereksperimen.
Intervensi cepat (first 90 days)
- Terapkan blameless post-mortems: aturan rapat evaluasi tanpa menyalahkan, fokus pada root cause & perbaikan. (Contoh praktik dari tim engineering/DevOps).
- Pemimpin memulai ritual: secara terbuka mengakui kesalahan pribadi dan pelajaran yang diambil (memodelkan perilaku).
- Ubah bahasa organisasi: dari “siapa salah” → “apa yang terjadi & bagaimana kita mencegahnya ke depan”.
Metrik pengukuran awal
- % pertemuan post-mortem yang menghasilkan daftar aksi tanpa menyebut orang (target: 100%).
- Hasil pulse survey soal “apakah saya merasa aman mengakui kesalahan” (skor netto).
- Jumlah masalah yang terdeteksi lebih awal vs yang tertutup (trend per kuartal).
(Sumber: HBR dan best practice praktik blameless culture). Harvard Business Review
2) Fenomena Silo (Unit sebagai Pulau) — mengapa ini racun eksekusi
Apa itu?
Silo terjadi ketika divisi/unit bekerja terpisah, punya tujuan sendiri tanpa integrasi yang nyata ke tujuan organisasi. Akibatnya alur kerja terputus-putus.
Tanda-tanda
- KPI unit berbeda dan kontradiktif (marketing dorong growth, operasi kejar efisiensi, keuangan block budget).
- Kurang ritual kolaborasi lintas fungsi (tidak ada daily/weekly cross-functional sync).
- “Tossing the work over the wall”: satu tim selesai pekerjaan lalu menyerahkannya tanpa kolaborasi.
Teori & referensi
Patrick Lencioni menempatkan inattention to results dan kurangnya trust antar-tim sebagai salah satu penyebab kegagalan tim dalam The Five Dysfunctions of a Team — silo adalah manifestasi praktis dari dysfunction tersebut. tablegroup.com
Dampak praktis
- Proyek lintas-fungsi molor, biaya naik, outcome tidak sinkron.
- Pelaksanaan strategi holistik gagal karena eksekusi fragmented.
Intervensi cepat
- Bentuk cross-functional squads untuk proyek-proyek prioritas (time-boxed, dengan mandat dan otoritas jelas).
- Standarisasi ritual: cross-team sprint review atau weekly ops sync untuk inisiasi dan penyelarasan.
- Sesuaikan KPI: tambahkan indikator lintas-fungsi (mis. NPS pelanggan + cycle time + cost to serve) yang mendorong kolaborasi.
Metrik pengukuran
- Jumlah inisiatif cross-functional yang mencapai milestones tepat waktu.
- Lead time antar-hand-off (harus turun).
- Net Promoter Score / kepuasan internal terhadap kolaborasi antar departemen.
3) Minimnya Tanggung Jawab Kolektif (Compliance vs Commitment)
Apa itu?
Organisasi yang menilai “sukses” lewat kepatuhan terhadap SOP (compliance) tetapi tidak menanamkan rasa kepemilikan atas hasil akhir (commitment). Orang melakukan tugas mereka, tapi bukan demi outcome bersama.
Tanda-tanda
- Bahasa pekerjaan: “saya sudah melakukan tugas saya” sebagai akhir diskusi.
- KPI fokus pada aktivitas bukan outcome (mis. jam kerja, jumlah meeting, bukan impact).
- Rendahnya engagement: karyawan tidak merasa tujuan organisasi juga tujuan pribadi mereka.
Data penting
Gallup melaporkan tren engagement global yang rendah — hanya sekitar 21% karyawan merasa engaged — dan menyatakan dampak ekonomi besar dari kurang engaged (efek terhadap produktivitas dan profitabilitas). Ini mengindikasikan rendahnya sense of ownership di banyak organisasi. Gallup.com
Dampak praktis
- Eksekusi mekanis: tugas dikerjakan, tapi tidak ada improvisasi/penyempurnaan saat hambatan muncul.
- Perbaikan berulang tidak terjadi — karena tidak ada pemilik yang peduli pada hasil akhir.
Intervensi cepat
- Ubah desain KPI: dari output → outcome. (Contoh: bukan “jumlah laporan” tapi “waktu rata-rata penyelesaian masalah pelanggan”).
- Program ownership onboarding: mulai dari hari pertama, jelaskan misi & bagaimana peran individu memengaruhi hasil.
- Sistem pengakuan & reward yang menghargai inisiatif dan perbaikan proses (bukan sekadar kepatuhan).
Metrik pengukuran
- Share of goals di level individu yang terikat ke outcome organisasi (vs aktivitas).
- Skor engagement/pulse survey khusus soal “saya merasa pekerjaan saya berkontribusi ke tujuan organisasi”.
- Jumlah ide perbaikan yang diusulkan & diimplementasikan oleh frontline (indicator of ownership).
4) Fenomena Lintas Sektor — bagaimana hambatan cultural ini muncul di berbagai konteks
Setiap sektor punya versi tersendiri dari masalah ownership:
- Korporat: Digital transformation sering gagal bukan karena teknologi, tetapi karena orang—karyawan garis depan tidak mengadopsi proses baru karena tidak merasa itu “milik mereka”. Penelitian McKinsey menampilkan bahwa sebagian besar transformasi gagal karena faktor people & leadership. McKinsey & Company
- Pemerintah / BUMN: Program yang dibuat di tingkat pusat bisa macet di lapangan karena birokrat atau pelaksana daerah merasa itu bukan tupoksi mereka—sehingga ownership tidak pernah terbentuk.
- NGO / Sosial Impact: Organisasi dengan visi sosial besar sering menghadapi tantangan disiplin eksekusi, koordinasi donor, dan penyerapan kapabilitas lokal—sehingga program berhenti walau niat baik ada.
- Startup: Banyak startup gagal scale karena tim tidak punya ownership terhadap produk/market fit; tanggung jawab kabur menyebabkan eksekusi lemah—CB Insights menyebut tim/people issues sebagai salah satu alasan utama kegagalan startup (tim yang tidak cocok, kurang eksekusi). (catatan: CB Insights menjabarkan banyak penyebab; ownership sering tumpang tindih dengan ‘team’ & ‘execution’ issues).
Intervensi lintas-sektor (prinsip umum)
- Fokus pada people & culture digitization, bukan hanya tool/tech stack.
- Terapkan model change management (Kotter): buat sense of urgency, bangun guiding coalition, dan enable action dengan menghilangkan hambatan struktural. Kotter International Inc
- Kustomisasi: pendekatan untuk pelayan publik akan berbeda taktiknya dengan startup—tetap gunakan prinsip ownership: role clarity, empowerment, dan feedback loop.
Cara Diagnosa Cepat: Checklist untuk pimpinan (5 menit)
- Apakah rapat evaluasi lebih sering mencari solusi atau mencari siapa yang salah? (blame)
- Adakah KPI yang melintasi fungsi untuk mendorong kolaborasi? (silo)
- Berapa % karyawan yang merasa pekerjaan mereka berdampak? (pulse engagement)
- Apakah pemimpin senior pernah mengakui kesalahan publik dan menjelaskan pelajaran yang diambil? (role model)
Jika jawaban banyaknya negatif → ada masalah ownership yang mendesak.
📍 Ownership: The Missing Link
Di titik ini, satu kesimpulan mulai jelas: masalah utama organisasi bukan strategi yang lemah, melainkan absennya ownership mindset.
Data demi data menegaskan hal ini. Menurut laporan Harvard Business Review (2019), lebih dari 70% inisiatif perubahan organisasi gagal mencapai targetnya. Ironisnya, sebagian besar kegagalan bukan disebabkan karena strategi yang buruk, melainkan karena lemahnya eksekusi yang berakar pada kurangnya rasa memiliki (ownership) dari orang-orang yang menjalankannya.
Jocko Willink dan Leif Babin dalam buku klasik mereka Extreme Ownership (2015) menegaskan:
“Leaders must own everything in their world. There is no one else to blame.”
Kalimat sederhana ini sarat makna. Ownership bukan hanya soal taking responsibility, tapi juga tentang kesediaan untuk mengambil kendali penuh, mencari solusi, dan menolak mencari kambing hitam.
Namun, mari kita luruskan. Ownership bukanlah konsep militeristik semata. Prinsip ini justru semakin relevan dalam dunia kerja modern yang penuh dinamika: hybrid workforce, kolaborasi lintas generasi, hingga kompleksitas digitalisasi.
🔑 Ownership sebagai Missing Link dalam Human Development
- Tanpa ownership, strategi berhenti di kertas.
Tidak peduli seberapa detail roadmap disusun, jika orang-orang yang menjalankannya tidak merasa bagian dari misi, strategi akan mati sebelum lahir. - Dengan ownership, strategi sederhana bisa menembus keterbatasan.
Banyak startup kecil membuktikan hal ini. Mereka mungkin tidak punya resources besar atau strategi yang tebal, tetapi memiliki tim dengan ownership tinggi—hasilnya mereka bisa melampaui batas yang dianggap mustahil. - Ownership = fondasi eksekusi yang berkelanjutan.
Teknologi, metode, dan tren manajemen akan terus berubah. Tapi mindset ownership memberi energi jangka panjang, membuat organisasi bisa beradaptasi sekaligus konsisten mengeksekusi.
🔄 Menuju Part 2
Pertanyaan penting pun muncul:
- Kalau begitu, apa sebenarnya makna ownership ini?
- Bagaimana ownership bisa dipahami bukan sekadar jargon, tetapi menjadi filosofi hidup dalam kepemimpinan dan organisasi?
- Apa hubungannya dengan human development di era modern?
👉 Jawabannya ada di Part 2: Definisi & Filosofi Extreme Ownership.