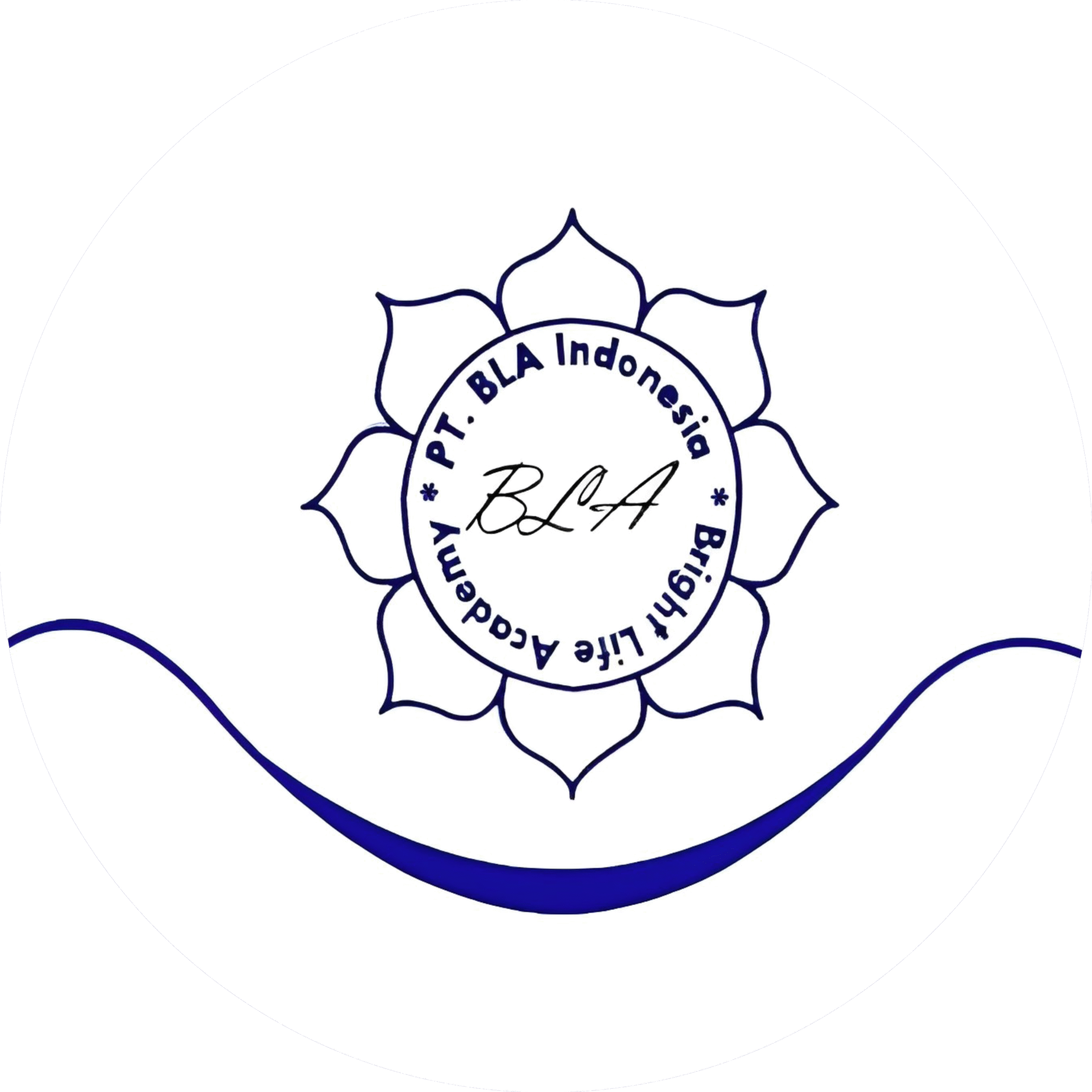Bayangkan sebuah rapat mingguan di sebuah perusahaan besar. Agenda sudah rapi di layar, pimpinan duduk di kursi utama, dan semua mata tertuju padanya. Ia membuka diskusi, lalu segera mendikte keputusan. Tim mendengarkan, mengangguk, mencatat, dan menunggu instruksi berikutnya. Tidak ada perdebatan, tidak ada eksplorasi ide, tidak ada ruang bagi kreativitas. Semua berjalan “efisien” sesuai prosedur.
Model ini pernah menjadi standar emas kepemimpinan. Di era industri yang relatif stabil, command & control—pemimpin yang memegang penuh arah, instruksi, dan kontrol—memang bisa memastikan keteraturan. Namun, dunia kerja kita hari ini sudah bergeser drastis.
- Artificial Intelligence menggantikan pekerjaan rutin dengan kecepatan tak terbayangkan. Tugas analisis data, penulisan, hingga coding kini bisa dilakukan mesin dalam hitungan detik.
- Generasi Z kini memasuki dunia kerja dalam jumlah signifikan. Mereka tumbuh dengan budaya digital, menginginkan suara dalam pengambilan keputusan, dan mencari makna di balik pekerjaan, bukan sekadar gaji.
- Hybrid work telah menjadi norma baru pasca-pandemi, membuat jarak fisik bukan lagi penghalang, tapi juga menantang cara tradisional mengelola kedekatan, kolaborasi, dan kontrol.
Di tengah perubahan besar ini, muncul pertanyaan mendasar:
👉 Apakah cara lama memimpin—command & control—masih relevan?
Jawabannya mulai terlihat dari data. Menurut laporan Deloitte Global Human Capital Trends 2023, 94% eksekutif percaya bahwa “kepemimpinan baru” dibutuhkan untuk menghadapi disrupsi. Namun ironisnya, hanya 23% organisasi yang merasa benar-benar siap untuk beradaptasi.
Dengan kata lain: mayoritas pemimpin menyadari ada gap besar antara kesadaran dan kesiapan. Inilah sinyal bahwa gaya kepemimpinan lama bukan hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi menghambat keberlangsungan organisasi.
Trend & Tantangan VUCA
Istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) sering kita dengar di ruang-ruang diskusi strategis. Namun, VUCA bukan sekadar jargon akademis; ia adalah realitas yang setiap hari dihadapi organisasi, baik di dunia korporasi, birokrasi, maupun NGO.
Mari kita bedah satu per satu:
1. Volatility (Volatilitas) – Kecepatan Perubahan yang Mengguncang
Teknologi dan pasar kini berubah dengan ritme yang jauh lebih cepat daripada kapasitas adaptasi sebagian besar organisasi.
- Contoh konkret: ChatGPT hanya butuh 5 hari untuk mencapai 1 juta pengguna, sedangkan Netflix butuh 3,5 tahun untuk pencapaian yang sama.
- Dampak: Produk dan model bisnis yang dahulu bertahan puluhan tahun kini bisa usang hanya dalam hitungan bulan. Menurut McKinsey, rata-rata umur perusahaan di indeks S&P 500 pada 1960-an adalah 61 tahun, tetapi kini hanya sekitar 18 tahun.
Volatilitas menuntut organisasi untuk memiliki daya tanggap instan, bukan sekadar rencana lima tahunan yang kaku.
2. Uncertainty (Ketidakpastian) – Dunia yang Tak Lagi Bisa Diprediksi
Kombinasi krisis geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi ekonomi global menciptakan ruang ketidakpastian yang semakin luas.
- Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran keras: rantai pasok global bisa berhenti total hanya dalam beberapa minggu.
- Konflik geopolitik seperti perang di Ukraina dan tensi di Asia Pasifik mengacaukan prediksi harga energi, pangan, dan logistik dunia.
- Deloitte menemukan bahwa lebih dari 70% CEO global merasa organisasi mereka belum siap menghadapi disrupsi geopolitik jangka panjang.
Ketidakpastian ini membuat prediksi berbasis tren historis semakin kurang relevan.
3. Complexity (Kompleksitas) – Masalah Tak Lagi Sederhana
Organisasi menghadapi masalah lintas dimensi: digitalisasi, keberlanjutan (sustainability), regulasi, dan ekspektasi stakeholder yang berlapis.
- Sebuah perusahaan yang ingin menerapkan energi hijau tidak hanya berhadapan dengan isu teknis (teknologi panel surya), tetapi juga ekonomi (biaya transisi), politik (insentif pemerintah), sosial (dukungan masyarakat), hingga regulasi internasional.
- Menurut World Economic Forum (2024), 80% pemimpin organisasi menyatakan bahwa kompleksitas regulasi lintas negara menjadi hambatan terbesar dalam ekspansi bisnis global.
Kompleksitas membuat solusi tunggal nyaris mustahil. Diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
4. Ambiguity (Ambiguitas) – Ketidakjelasan Aturan Main
Dalam banyak kasus, organisasi baru menyadari aturan main ketika permainan sudah berlangsung.
- Contoh di sektor digital: regulasi terkait AI, data privacy, dan fintech selalu tertinggal dari inovasi. Akibatnya, perusahaan bergerak dalam area abu-abu yang penuh risiko.
- Pemerintah pun sering menghadapi ambiguitas saat harus merespons cepat, padahal panduan kebijakan masih samar.
Ambiguitas membuat banyak pemimpin merasa seperti “berjalan dalam kabut”—tidak jelas arah dan konsekuensinya.
Realitas Pahit VUCA
Banyak organisasi besar telah tumbang karena gagal membaca realitas ini. Nokia, Kodak, Blockbuster adalah simbol betapa “keangkuhan stabilitas” bisa menjadi jebakan. Di sektor publik, birokrasi sering dianggap lamban, rigid, dan tidak responsif terhadap ekspektasi masyarakat yang kian kritis dan demanding.
VUCA memaksa kita untuk mengakui bahwa:
👉 kepemimpinan lama yang berpusat pada kontrol dan kepatuhan tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman.
Kelemahan Model Command & Control
Model kepemimpinan tradisional—yang menempatkan pemimpin sebagai pusat instruksi, pengendali, sekaligus pengambil keputusan utama—dulu dianggap sebagai formula sukses. Tetapi dalam konteks VUCA, model ini justru menjadi batu sandungan.
Setidaknya ada tiga kelemahan utama yang membuat gaya command & control semakin ketinggalan zaman:
1. Pemimpin sebagai pusat keputusan → lambat dan tidak adaptif
Dalam struktur hierarki kaku, setiap keputusan penting harus melewati berlapis otorisasi.
- Contoh birokrasi: satu izin bisa butuh 5–7 tanda tangan pejabat. Pada akhirnya, ketika izin selesai, konteks lapangan sudah berubah.
- Di perusahaan: proses persetujuan berjenjang membuat organisasi kehilangan speed untuk merespons peluang.
Padahal, kecepatan adalah faktor diferensiasi. Menurut Boston Consulting Group (2023), perusahaan yang mampu mengambil keputusan 40% lebih cepat dibanding kompetitornya cenderung menghasilkan pertumbuhan pendapatan 2x lipat.
👉 Artinya: command & control membuat organisasi kehilangan momentum.
2. Pemimpin menahan ide → tim menjadi pasif
Dalam model lama, pemimpin sering merasa dirinya harus menjadi “sumber ide terbaik”. Akibatnya, gagasan dari tim jarang naik ke permukaan.
Dampaknya bisa dilihat dari data: studi Gallup (2022) menemukan hanya 21% karyawan global yang merasa engaged di tempat kerja. Lebih dari separuh karyawan merasa opini mereka “tidak diperhitungkan”.
Hasilnya?
- Karyawan datang hanya untuk bekerja sesuai instruksi, bukan untuk berinovasi.
- Ide-ide segar sering kali terkubur sebelum sempat diuji.
- Organisasi kehilangan potensi intelektual terbesar: collective intelligence.
👉 Pemimpin yang menahan ide sebenarnya sedang menyusutkan kapasitas timnya sendiri.
3. Pemimpin menekankan kepatuhan → hilangnya kreativitas
Command & control pada akhirnya menciptakan budaya compliance over creativity.
- Kepatuhan dianggap lebih penting daripada keberanian mengambil risiko.
- Eksperimen dan improvisasi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas.
- Karyawan belajar untuk “main aman” daripada mencoba terobosan.
Padahal, di era disrupsi, inovasi bukan sekadar keunggulan kompetitif, melainkan oksigen untuk bertahan hidup.
Contoh nyata: startup digital lebih lincah dibanding perusahaan mapan justru karena mereka mendorong ide dari bawah. Di banyak startup, prinsip fail fast, learn faster menjadi norma. Sebaliknya, perusahaan besar dengan struktur hierarkis justru kerap terjebak dalam “paralisis analisis” sebelum bertindak.
Gaya kepemimpinan command & control mungkin pernah relevan di era stabilitas industri. Tetapi kini, ia menghasilkan organisasi yang lambat, pasif, dan miskin inovasi—tiga hal yang persis berlawanan dengan kebutuhan organisasi di era VUCA.
👉 Dengan kata lain, model kepemimpinan lama bukan hanya ketinggalan zaman, tetapi juga berisiko membuat organisasi kehilangan relevansi.
Bridge ke Konsep Baru
Semua analisis di atas membawa kita pada pertanyaan mendasar:
👉 Jika model kepemimpinan lama tidak lagi cukup, lalu apa alternatifnya?
Banyak organisasi masih terjebak pada asumsi klasik: solusi terletak pada mencari pemimpin yang paling pintar, paling berpengalaman, atau paling visioner. Seolah-olah keberhasilan organisasi ditentukan oleh “satu otak terbaik di ruangan.”
Namun realitas membuktikan sebaliknya. Dalam dunia yang bergerak terlalu cepat dan kompleks, tidak ada satu pun pemimpin, betapapun briliannya, yang mampu memahami semua hal sendirian. Harvard Business Review pernah menulis, “The lone genius leader is a myth. Sustainable success is always collective.”
Artinya, kehebatan pemimpin bukan lagi diukur dari kecerdasan pribadinya, tetapi dari kemampuannya menggandakan kecerdasan orang lain. Pemimpin yang efektif bukanlah the smartest in the room, melainkan the one who makes everyone in the room smarter.
Dan di sinilah kita menemukan jawaban: Multiplier Leadership.
Konsep yang diperkenalkan oleh Liz Wiseman ini menawarkan pendekatan radikal tetapi relevan: seorang pemimpin sejati adalah Multiplier—ia mampu memperluas kapasitas tim, memicu energi, dan menciptakan lingkungan di mana ide tumbuh lebih cepat daripada hambatan.
Alih-alih menguras energi tim, seorang Multiplier justru menjadi katalis yang membuat seluruh organisasi lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih inovatif.
Inilah titik balik dari paradigma lama ke paradigma baru:
- Dari command & control → menuju empower & multiply.
- Dari pemimpin pusat segala jawaban → menuju pemimpin yang membangkitkan jawaban dari timnya.
- Dari kepatuhan buta → menuju partisipasi penuh makna.
👉 Dan inilah yang akan kita kupas lebih dalam di Part 2: Framework Multipliers—bagaimana sebenarnya lima disiplin Multipliers bekerja, dan mengapa model ini menjadi kunci untuk mengembangkan kapasitas SDM di era VUCA.